Dari Akses Menuju Kesetaraan: Pendidikan Indonesia yang Mulai Berdaya
Oleh: Shinta Nur| Pemerhati Pendidikan Asal Bandung

Revitalisasi bukan hanya membangun tembok, tapi memulihkan martabat ruang belajar.
DARI kejauhan, denting palu bersahutan dengan tawa anak-anak yang berlarian di halaman sekolah. Di bawah langit cerah lereng Gunung Muria, bangunan tua yang dulu retak kini berdiri gagah dengan cat baru, jendela-jendela lebar, dan papan tulis yang bersih dari debu. Di salah satu dindingnya, tergantung tulisan tangan sederhana: “Belajar adalah harapan.”
Pemandangan seperti itu dulu terasa langka. Kini, ia menjadi wajah baru yang mulai menjamur di berbagai penjuru Nusantara. Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, sekolah-sekolah yang sempat nyaris ditinggalkan kini hidup kembali—berkat program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang telah berjalan setahun terakhir.
Melalui alokasi Rp16,97 triliun, pemerintah berhasil memperbaiki 15.523 satuan pendidikan, melampaui target awal 10.440 sekolah. Tapi lebih dari sekadar pencapaian angka, yang tumbuh adalah rasa kebersamaan: pendidikan yang dibangun masyarakat, untuk masyarakat.
Di Kudus, guru dan warga saling bahu-membahu merenovasi ruang kesenian serta membangun toilet ramah disabilitas. Sementara di Kota Batu, dana revitalisasi senilai Rp1,7 miliar bukan hanya memperbaiki 293 sekolah, tapi juga menghidupkan kembali roda ekonomi desa. Tukang, pengrajin, hingga penjual bahan bangunan lokal ikut menikmati dampaknya.
Seperti dikatakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat meninjau proyek di Jawa Tengah. “Revitalisasi bukan hanya membangun tembok, tapi memulihkan martabat ruang belajar.”
Kalimat itu terasa benar di lapangan. Sebab di banyak tempat, sekolah kini tak lagi sekadar bangunan fisik, melainkan ruang tumbuhnya harapan baru. Saat orang tua membantu mengecat ruang kelas, guru menata ulang pojok baca, dan murid menanam bunga di halaman sekolah, di sanalah pendidikan kembali menjadi milik bersama—bukan hanya urusan pemerintah, tapi urusan seluruh bangsa.
Langkah besar itu kini bersambung dengan babak baru: Digitalisasi Pendidikan Nasional.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025, pemerintah memperluas akses pembelajaran digital ke lebih dari 285.000 satuan pendidikan, dari PAUD hingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Ruang belajar kini tak lagi berhenti di papan tulis.
Di Papua, televisi lokal menyiarkan pelajaran untuk anak-anak tanpa sinyal internet. Di Kalimantan Utara, radio komunitas berubah menjadi kelas sore yang menyatukan suara dan ilmu. Dan di Sulawesi Tengah, tablet sederhana membuka dunia baru bagi siswa desa yang kini mengenal Kurikulum Merdeka lewat layar kecil di genggaman.
Data BPS (2025) menunjukkan, 68% sekolah di wilayah 3T telah memiliki akses internet—naik 14% dari tahun sebelumnya. Namun, 32% sisanya masih berjuang dengan koneksi terbatas, mengingatkan bahwa pemerataan digital masih merupakan perjalanan panjang.
Untuk memperkuat langkah ini, pemerintah menyalurkan 288.000 papan interaktif digital (IFP) ke sekolah-sekolah, mendorong transformasi belajar yang lebih visual dan kolaboratif.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut, “Teknologi bukan hanya alat bantu, tapi jembatan menuju kesetaraan kualitas.”
Dampaknya mulai terasa. Guru-guru di sekolah seperti SMKN 1 Kudus kini memanfaatkan perangkat digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih hidup. “Anak-anak jadi berani berpendapat dan aktif berdiskusi,” tutur Puji Basuki, guru Bahasa Inggris di sekolah itu.
Sementara Muhammad Aflah Hilmanunulya, siswa kelas XII, tersenyum saat ditanya perubahan yang ia rasakan:
“Sekarang, belajar itu seperti jendela yang terbuka lebar.”
Dari cerita mereka, terlihat jelas bahwa perubahan tak lagi berhenti pada kebijakan, tapi menjelma menjadi pengalaman nyata. Digitalisasi bukan hanya soal koneksi internet atau perangkat, tapi tentang membuka kesempatan—tentang bagaimana setiap anak, di manapun ia lahir, punya hak yang sama untuk bermimpi.
Tentu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada guru yang belum terlatih, sekolah yang tertinggal sinyal, dan keluarga yang butuh pendampingan digital.
Namun langkah-langkah kecil yang kini nyata di lapangan membuktikan satu hal: kesetaraan bukan cita-cita yang jauh, tapi proses yang sedang tumbuh di depan mata.
Dan di balik setiap gedung baru dan layar digital yang menyala, ada keyakinan yang sama—bahwa pendidikan yang berdampak selalu dimulai dari hati yang percaya pada masa depan.
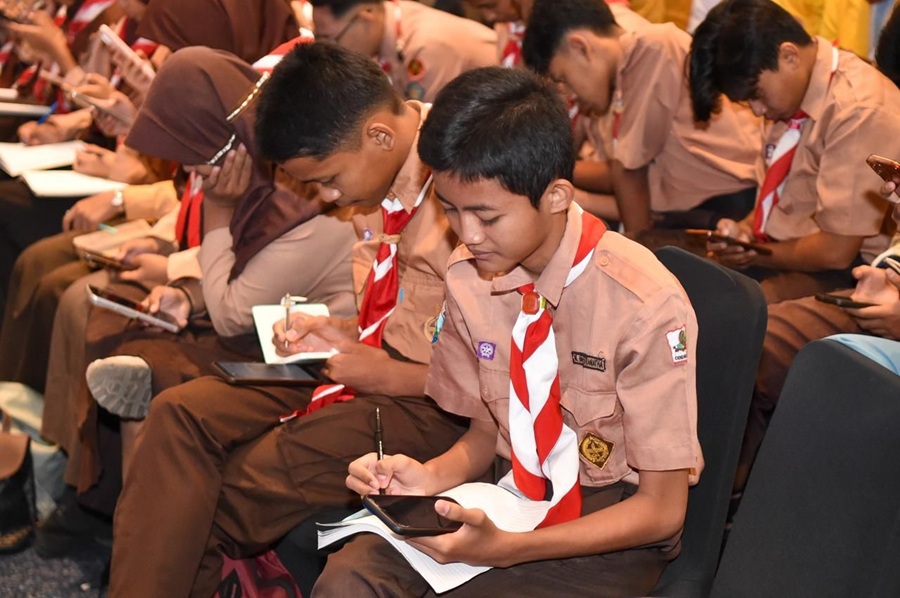
Seminar anak sekolah bersama kemendikdasmen. (Foto: Ist/Shinta Nur)
Guru Berdaya, Murid Terbuka: SDM yang Menjadi Arah Perubahan
Di setiap ruang kelas di negeri ini, selalu ada dua wajah yang menentukan arah masa depan: guru yang mengajar dengan hati dan murid yang belajar dengan semangat.
Mereka adalah nadi dari sistem pendidikan — sosok yang menjaga api perubahan tetap menyala, bahkan ketika kebijakan berubah dan zaman bergerak cepat.
Tahun 2025 menjadi penanda penting ketika pemerintah mulai menegaskan kembali fondasi pendidikan: bahwa perubahan sejati tidak lahir dari gedung baru, melainkan dari manusia yang tumbuh di dalamnya.
Lewat kebijakan besar yang berfokus pada pemberdayaan guru, negara berusaha mengembalikan makna profesi mulia ini ke tempat yang semestinya — sebagai ujung tombak peradaban belajar.
Lebih dari Rp13,2 triliun digelontorkan untuk memperkuat kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Hasilnya mulai terasa:
785 ribu guru non-ASN kini menerima tunjangan profesi Rp2 juta per bulan,
253 ribu guru PAUD nonformal memperoleh Bantuan Subsidi Upah Rp300 ribu,
804 ribu guru mengikuti Program Profesi Guru (PPG) untuk memperdalam pedagogi,
dan 16.197 guru diberi kesempatan melanjutkan studi ke jenjang S1/D4 — bukti bahwa peningkatan mutu kini bukan lagi wacana, tapi gerakan nyata.
Sejak Agustus 2025, insentif tambahan Rp2,1 juta juga diberikan kepada guru non-ASN selama tujuh bulan berturut-turut, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka yang menjaga nyala belajar meski di tengah keterbatasan.
Sementara bagi guru ASN, dukungan hadir melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik senilai Rp70 triliun, yang dialokasikan dalam tiga bentuk utama:
Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 1,52 juta guru,
Dana Tambahan Penghasilan (DTP) bagi 332 ribu guru, dan
Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi 62 ribu pendidik di wilayah 3T.
Di balik angka-angka itu, ada kisah yang jauh lebih manusiawi: guru-guru yang kini lebih berani bereksperimen di kelas, menggunakan project-based learning, menciptakan media ajar digital, dan memanfaatkan papan interaktif hasil distribusi nasional.
Di Banyumas, seorang guru IPA membuat video eksperimen sains sederhana agar siswanya lebih memahami konsep praktis.
Di Fakfak, pelatihan daring menjadi ajang berbagi ide lintas provinsi.
Semua bergerak, dengan satu tujuan: membuat pembelajaran kembali hidup.
Namun, di tengah kemajuan itu, masih ada catatan reflektif.
Survei Balitbang Kemendikbud (2025) menunjukkan 42% guru di wilayah timur terkendala sinyal saat pelatihan daring, dan 37% guru mengaku waktu refleksi mereka terkikis oleh beban administratif.
Pengamat pendidikan Najeela Shihab mengingatkan,
“Guru perlu ruang aman untuk bereksperimen, bukan hanya ruang untuk mengisi formulir.”
Tanpa ruang berpikir yang bebas, kesejahteraan finansial hanya akan menjadi angka, bukan kemerdekaan.
Kebijakan pemberdayaan guru berjalan beriringan dengan afirmasi bagi murid.
Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau 18,5 juta siswa dengan anggaran Rp13,5 triliun, sementara Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) senilai Rp127 miliar memastikan 4.679 siswa 3T tetap bersekolah.
Tak ketinggalan, Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) menyalurkan Rp59,3 triliun kepada 422.106 sekolah dan lebih dari 50 juta peserta didik, menjaga agar kegiatan belajar tetap berjalan tanpa membebani keluarga.
Di sisi kebijakan, reformasi sistem seleksi murid juga membawa angin segar.
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang menggantikan PPDB mendapat sambutan positif publik.
Berdasarkan survei Katadata Insight Center (KIC, 2025):
80% masyarakat sudah mengenal sistem ini,
88% menilai lebih baik, dan
90% menyebut sesuai harapan.
SPMB menghadirkan transparansi dan keadilan baru.
Lebih dari 91% responden menilai sistem ini memperluas kesempatan bagi siswa berprestasi, keluarga kurang mampu, dan penyandang disabilitas untuk bersaing secara adil.
Namun demikian, 24,9% masyarakat menilai sosialisasi masih perlu diperkuat, dan 10,2% melaporkan kendala teknis dalam pendaftaran daring — sebuah pengingat bahwa perubahan selalu datang bersama ruang perbaikan.
Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu keyakinan sederhana:
bahwa pendidikan bukan proyek pemerintah, melainkan perjalanan kolektif bangsa untuk menumbuhkan manusia yang berdaya.
Dan di tangan para guru yang tak lelah belajar, murid yang tak berhenti bermimpi, serta kebijakan yang terus mendengar, pendidikan Indonesia perlahan menemukan bentuk barunya — lebih adil, lebih hidup, dan lebih manusiawi.
Menegakkan Standar, Menumbuhkan Karakter: Arah Baru Menuju Mutu
Di antara deru pembangunan dan euforia digitalisasi, ada satu hal yang sering terlupakan: bahwa pendidikan sejatinya bukan sekadar membangun ruang belajar, melainkan membentuk manusia yang berpikir dan berkarakter.
Tembok sekolah bisa dicat ulang, jaringan internet bisa diperluas, tetapi mutu dan nilai hanya bisa ditumbuhkan — perlahan, dari ruang-ruang belajar yang jujur dan reflektif.
Kesadaran inilah yang mulai tumbuh kuat dalam arah kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah kini berupaya menata ulang cara bangsa ini mengukur hasil belajar. Melalui Tes Kompetensi Akademik (TKA), sistem penilaian dirancang ulang untuk menilai cara berpikir, bukan hanya seberapa banyak yang dihafal.
Langkah ini menandai pergeseran penting — dari paradigma ujian sebagai penentu kelulusan menuju alat ukur kualitas belajar yang lebih manusiawi.
Meski baru bersifat sukarela, gagasan ini mendapat sambutan luas.
Hasil survei Katadata Insight Center (2025) menunjukkan 87,6% orang tua memahami pentingnya TKA sebagai instrumen objektif untuk menilai hasil belajar, sementara 9 dari 10 responden mendukung penerapannya dalam seleksi pendidikan lanjutan.
Namun, di balik angka dukungan itu, tersimpan pekerjaan rumah yang tak kecil. Hanya 46,2% orang tua yang tahu bahwa TKA tidak wajib, dan 21,6% yang memahami bahwa tes ini bukan pengganti Ujian Nasional.
Artinya, di tengah perubahan yang baik, masih ada ruang besar untuk memperkuat literasi publik.
Sebab kebijakan, betapapun visioner, akan kehilangan daya jika tak diiringi pemahaman bersama.
Karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan program edukasi publik agar masyarakat memahami esensi TKA — bahwa yang diuji bukan hafalan, tetapi kemampuan berpikir kritis, bernalar, dan memahami konteks.
“Yang terpenting, TKA harus menjadi ukuran kemampuan berpikir, bukan sekadar hafalan,” ujar Satria Triputra, Research & Analytics Manager Katadata Insight Center.
Pemerintah pun berencana memperluas pelaksanaan TKA ke jenjang SD dan SMP dengan melibatkan dinas pendidikan daerah.
Tujuannya jelas: agar setiap butir soal tidak hanya mencerminkan standar nasional, tetapi juga menggambarkan konteks lokal — budaya, bahasa, dan pengalaman anak-anak di daerah.
Dengan pendekatan itu, standardisasi tidak lagi berarti menyeragamkan, melainkan menegaskan bahwa mutu bisa setara dalam keberagaman.
Karena bangsa yang besar bukan yang memiliki sekolah paling megah, melainkan yang mampu memastikan setiap anak — di desa, pesisir, maupun kota — memiliki kesempatan yang sama untuk berpikir, tumbuh, dan bermimpi.
Menjahit Harapan di Setiap Ruang Kelas
Setahun terakhir, pendidikan Indonesia seolah menemukan denyutnya kembali.
Di antara gedung-gedung sekolah yang baru direnovasi dan layar-layar digital yang mulai menyala di ruang kelas pelosok, tumbuh kisah-kisah kecil yang jauh lebih besar dari sekadar angka capaian.
Pendidikan tak lagi hanya urusan administrasi atau laporan kinerja, melainkan perjalanan batin sebuah bangsa yang sedang belajar menjadi adil bagi anak-anaknya sendiri.
Di setiap sudut negeri, dari ruang kelas sederhana di Pulau Sabu hingga laboratorium digital di jantung Jakarta, perubahan itu mulai terasa nyata.
Guru bukan sekadar pengajar, tetapi penenun masa depan. Mereka menjaga bara semangat di tengah keterbatasan, mengubah papan tulis usang menjadi panggung ide dan keberanian berpikir.
Sementara murid-muridnya, dengan mata berbinar di depan tablet sederhana atau buku lusuh yang diwariskan, memetik satu pelajaran penting: bahwa belajar adalah bentuk paling nyata dari harapan.
Revitalisasi satuan pendidikan telah menghadirkan ruang belajar yang lebih manusiawi—tempat anak-anak merasa aman untuk bermimpi.
Digitalisasi menjembatani jarak antarwilayah, membuka jalan bagi pemerataan akses ilmu yang dulu terasa mustahil.
Dan di saat yang sama, kebijakan afirmatif memastikan tak ada anak yang tertinggal hanya karena ia lahir di tempat yang jauh atau dari keluarga sederhana.
Seperti diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat kunjungan kerjanya di Kudus:
“Pendidikan bukan urusan birokrasi semata, melainkan kerja bersama untuk memastikan setiap anak Indonesia punya hak yang sama untuk bermimpi dan mewujudkannya.”
Pernyataan itu terasa bukan sebagai slogan, melainkan cermin dari gerakan sosial yang kini tumbuh pelan tapi pasti.
Dari tangan-tangan guru yang sabar hingga komunitas orang tua yang gotong royong, pendidikan Indonesia sedang menulis bab barunya — bukan tentang kesenjangan, melainkan tentang keberanian untuk menyetarakan.
Kini, di setiap tawa murid, di setiap papan interaktif yang menyala, dan di setiap kelas kecil yang kembali hidup, kita menyaksikan perubahan itu menjadi nyata.
Pendidikan bukan lagi mimpi jauh yang hanya dimiliki sebagian orang, tetapi kenyataan yang mulai tumbuh di banyak penjuru negeri — menjahit martabat dan masa depan bangsa, satu ruang kelas demi satu ruang kelas.
Editor: Maji
